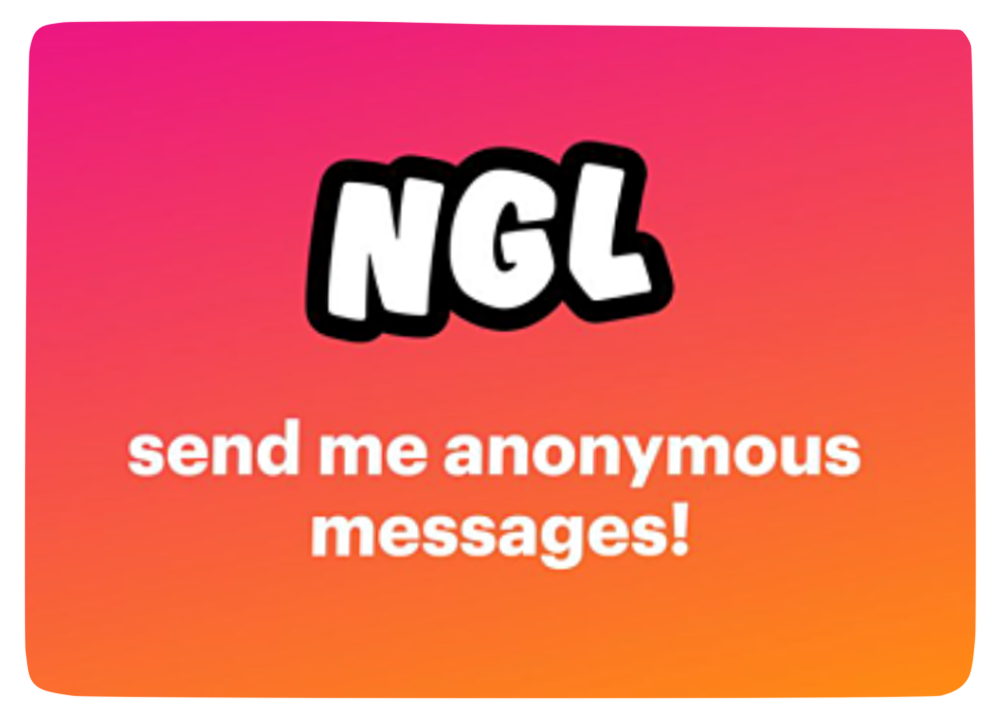Rahh,
Selamat malam; barangkali rembulan masih bercahaya untukmu. Walaupun malam ini dia sembunyi di balik awan itu—persis seperti kemarin, waktu kita makan mie ayam di Kota Tua, yang separuhnya kau berikan padaku.
Lha... padahal baru kemarin aku mengirimkan satu surat untukmu; sekarang aku ingin kirimkan satu lagi. Tidak tahu, entah apa alasannya... mungkin karena aku tahu sekarang ada yang menunggu-nunggu untuk membacanya—atau mungkin juga tidak. Aku sengaja menulis ini untuk kau baca sebelum tidur. Maka, kau pun memutar musiknya sebelum membaca suratku ini: Clair de Lune by Claude Debussy, yang sengaja aku pilih untuk mengiringi bacaannya. Mungkin sekali karena aku pikir lebih sesuai untuk kau dengar sambil membaca surat ini, yang atmosfernya—atau entah apanya—aku rasa cocok dengan suratku. Ini berarti bahwa ada juga sesuatu yang mengikat kata dan musiknya menjadi satu.
Rahh, kau tahu, akhir-akhir ini aku punya kebiasaan baru: memberi makan kucing liar yang kutemui sepanjang jalan pulang kerjaku—entah itu di sepanjang Jalan Sudirman, di stasiun, atau di Kebun Raya Bogor. Entahlah... apapun niatnya yang tersembunyi di hatiku, aku hanya ingin ada bagian untukku dari nikmat yang Rabb Semesta Langit dan Bumi berikan untuk kucing-kucing itu. Entahlah... aku hanya ingin sedikit saja apa yang diberikan Rabb Langit dan Bumi padaku jadi kabar gembira untuk mereka. Maka, senanglah hati mereka; lalu senang juga hatiku... walaupun aku sebenarnya tidak tahu apa yang dipikirkan kucing-kucing liar itu.
Satu kebiasaan lagi, Rahh. Aku selalu membaca cerita Ramayana sepanjang jalan di kereta—membacanya sambil duduk, sambil berdiri, sambil berdesak-desakan; sambil mendengarkan Chopin; sambil mendengarkan Payung Teduh; atau sambil mendengar decitan roda kereta dan bunyi tutup-buka pintu kereta. Aku suka saja membacanya... entah karena apa. Tapi aku pastikan bukan karena aku bosan, lalu membacanya hanya sebagai pengusir boring; bukan juga karena aku kebetulan membawa bukunya di tasku setiap hari.
Mungkin saja aku membacanya karena... hmmm... yahh... hmmmmmm...ah, entahlah... seperti ada yang ganjil. Padahal baru sehari dia kembali ke Jogja.
Aku akan menahan diri semampuku; aku akan menyimpan segala sesuatunya hingga entah nanti ketemu lagi. Setiap kali aku tulis sesuatu—kuhapus. Kutulis lagi—lalu kuhapus lagi. Siklus itu berulang beberapa kali sampai akhirnya aku tidak jadi mengirim pesannya vi—
Lho... kok aku jadi cerita sampai sini, Rahh? Hahaha. Anyway—aduh, aku lupa mau bilang apa. Kau tahu, aku bahkan menuliskan ini padamu sambil berdiri di kereta, pas pulang dari kantor, dan di tangan kiriku ada Rahvayana. Musiknya pas sekali, Rahh. Aku sedang mendengarkan Living on a Jet Plane—atmosfernya sama dengan suasana lagunya.
Rahh, aku dapat vibes itu lagi... vibes yang kukira sudah kutinggalkan di tempat yang lautnya jernih dengan terumbu karang warna-warni. Sekarang aku merasakannya lagi, saat musiknya memainkan Kenshi Yonezu... ahh, sedihnya. Bukan sedih dalam artian yang buruk—malahan ini lebih baik jika aku sedih karenanya. Sebab, mungkin itu tanda kalau hatiku masih ada di sana; dan itu baik.
Aku ingat saat yang paling aku rindu, walaupun saat mengalaminya dulu, aku sebenarnya biasa saja. Rasa capek yang paling indah. Satu-satunya—or salah satu—rasa capek yang aku senang karenanya. Saat capek itu berarti meringankan beban dan menyenangkan hati Mama dan Bapa. Aku rasa itu di antara hal-hal yang benar-benar punya harga yang nyata di sisi-Nya. Entah itu capek karena mengantar Mama belanja; rasa capek membantu Bapa memperbaiki sesuatu atau mengangkat sesuatu; atau apapun itu yang buat mereka senang. Bahkan, aku rela memberikan semuanya.
Ya sudah, sepertinya sampai sini saja suratku padamu, aku sudah mulai ngantuk, Rahh.
Selamat malam.
—Rama
Previous Next