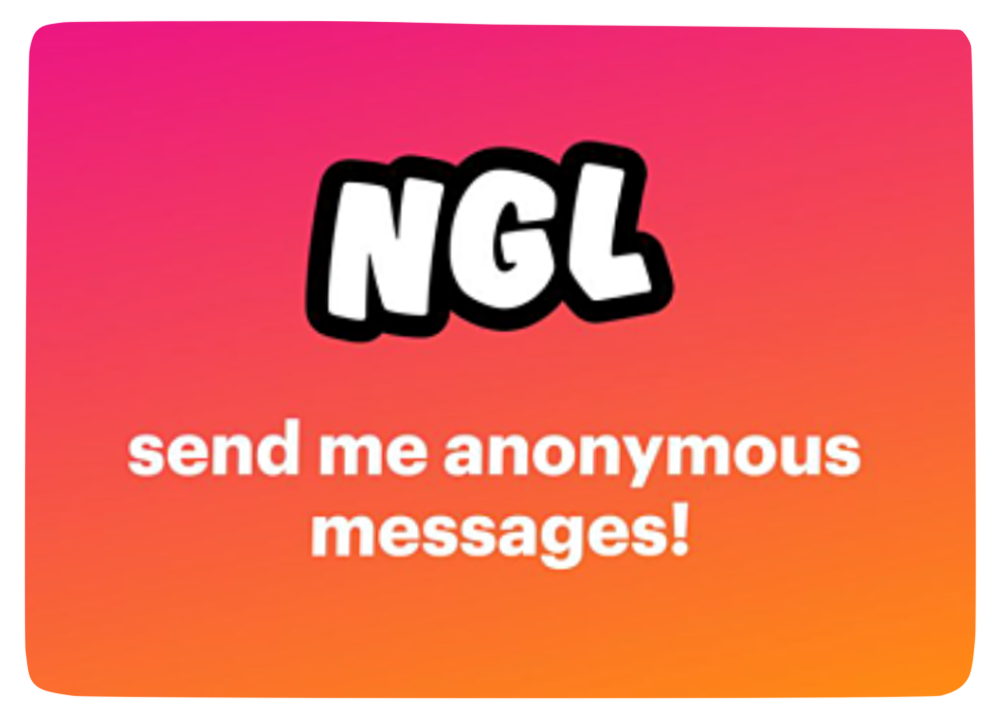Selamat malam, Sinta. Barangkali rembulan masih bersinar untukmu malam ini.
"Kamu ini lebay, Ram," mungkin begitu komentarmu ketika pertama kali membaca surat yang akhirnya sampai padamu itu. Tidak ada, rasanya, ucapan yang lebih dia syukuri. Ia suka dianggap lebay hanya kalau yang mengucapkannya Sinta—sebab ya memang lebay, mau apa lagi. Ia sering melawan pendapat itu dengan berbisik pada dirinya sendiri, "Apa nggak boleh nulis yang lebay?"
"Kamu nulis karena capek, kan, Ram?"
"Kata siapa? Aku nulis karena kangen, atuh..."
"Boong."
"Apanya?"
"Yaa kamu, boong... kamu nulis karena capek sama duniamu itu, kan?"
"Yaa... kan kamu."
"Masih boong... kamu nulis karena capek, bukan karena aku."
"Dibilang karena kangen."
"Yaah, kamu kalau capek aja baru kangen, kan?"
"Setengah benar."
Entahlah, Sinta. Aku capek sekaligus kangen—gimana dong?
Tenang saja sintaku, aku masih dan akan tetap sama, yang menulis surat untukmu, menyukaimu dengan segala tiba-tibanya.
Cantik, sih, cantik kamu itu. Apalagi saat aku memperhatikanmu dengan seksama sambil kita menyusuri pelataran candi. Aku menceritakan kisah Ramayana yang terpahat di relief dinding itu, dan kamu merekamnya dengan ponselmu—rekaman yang masih sering aku putar berulang kali sampai sekarang. Kita berjalan pelan, cahaya matahari jatuh tepat di wajahmu. Semakin kamu tersenyum, semakin aku hanyut. Siapa pun akan terpana saat kedua mata itu menatap sambil tersenyum manis.
Ingat tidak, Sinta, saat pertama kali kita bertemu lagi setelah sekian lama? Hari itu bergerak dalam irama yang aneh—siangnya kita ke candi, sorenya kita presentasi, lalu malamnya Kijang Kencana itu. Melodi di kepalaku sejak saat itu, Sinta.
Kadang dia muncul sebagai progresi minor yang meredup, kadang dalam staccato yang gelisah, kadang juga sebagai disonan—nyaris seperti pianist frustrasi tengah menghantam tuts tanpa peduli harmoni.
Tapi lebih sering dia datang sebagai arpeggio yang ringan—cascade yang turun bertahap seperti air terjun kecil, seperti Clair de Lune mengiringimu membaca ini. Lalu beberapa kali, ada loncatan notes yang melayang ke atas, saling sahut-menyahut, tak bisa menahan kegembiraannya. Sesekali dia seperti melodi lonceng bambu dan kaca yang diterpa angin sepoi.
Dan aku tidak pernah berniat memberhentikan melodinya. Terlintas di kepalaku pun tidak pernah. Tapi banyak hal lain yang mengisi kepalaku, Sinta. Tentang dirimu. Iya, selalu tentang dirimu.
Malam ini entah kenapa aku tidak bisa tidur, Sinta. Setelah mengobrol denganmu tadi, kepalaku penuh dengan ini-itu.
Mungkin agar bisa cepat terlelap, akan kutuliskan dongeng ini, sebagai pengantar tidurku yang mungkin kamu bisa membacakannya untukku kapan-kapan.
Kamu selalu suka kalau aku mendongeng, ya kan, Sinta? Mungkin kamu malah menikmati ekspresi wajahku ketika sedang berpikir-berpikir mengarang kelanjutan cerita dongengnya sehingga tampak selaras dengan pertanyaanmu, kan, Sinta?
Apakah ada yang ingin kamu tanyakan lagi padaku, Sinta?
Hmm... misalnya kenapa Rahwana pergi menculik dewinya menggunakan kijang kencana, bukannya menggunakan Lamborghini atau apalah?
Atau seberapa indah Argasoka yang disiapkan Rahwana khusus untuk mengurung dewinya?
Hmm... misalnya kenapa Rahwana harus menyuruh Marica menjelma jadi kijang kencana untuk memikat Sinta, bukannya langsung datang dengan pusaka saktinya yang bisa mengalahkan dewa? Atau mengapa dia menyiapkan Argasoka dengan segala kemegahannya—taman yang penuh pohon asoka dan bunga-bunga langka—padahal tahu bahwa Sinta tak akan pernah melihatnya sebagai surga, melainkan penjara?
Ah, Sinta, kamu pasti tak tertarik bertanya tentang hal ini. Kamu pasti lebih suka bertanya "Apa yang Rama rasakan saat pertama kali menerima kalung Subali dari Hanoman sebagai bukti bahwa dewinya masih hidup di Alengka?"
Atau mungkin "Mengapa Sinta menolak tawaran Hanoman untuk menyelamatkannya langsung dari Argasoka, malah memilih menunggu Rama datang sendiri menjemputnya?"
Iya kan, Sinta?
Begini, Sinta. Hanoman itu bukan kera biasa. Dia putra Dewa Bayu, dewa angin. Dia bisa terbang melintasi samudra yang lebarnya ratusan yojana tanpa jeda. Dia bisa menyusut sekecil nyamuk atau mekar setinggi gunung. Tenaganya bisa melumat ribuan raksasa sekaligus.
Maka malam itu, setelah Hanoman menyerahkan cincin Rama dan menyaksikan linangan air mata Dewi Sinta, Hanoman menawarkan untuk menggotong Dewi Sinta pulang saat itu juga.
Hanoman bisa saja menyelundupkan pujaan hati Rama keluar tanpa hambatan, wong siapa aja tumbang di hadapannya, apalagi cuma anak buah kelas teri. Dewi Sinta bisa menumpang di punggungnya, menerobos awan, menyeberangi samudra, dan mendarat di Ayodya sebelum fajar menyembul. Tak ada satu pun raksasa di Alengka yang sanggup menghadangnya.
Dhilalah, Dewi Sinta tetap membatu—hanya Rama yang boleh membawanya pulang.
Aduh, dongengku sudah terlampau panjang, Sinta. Aku sendiri sudah hampir terlelap sambil menuturkan ini.
Kamu juga tidurlah, Sinta.
Sebelum kamu memejamkan mata bersama langit-langit bintang yang semoga menggambarkan senyumku, cukuplah kamu ketahui bahwa sekalipun Rama tidak pernah menyuruh Hanoman untuk menjemput kekasihnya, dia hanya memerintahkan kera putih itu untuk mengecek keadaan dewinya, lalu Rama berniat untuk menyelamatkannya sendiri.
Tidurlah, Sinta.
Sebelum kamu terlelap bersama langit-langit yang semoga menggambarkan tangisku, cukuplah kamu ketahui bahwa Dewi Sinta tidak pernah benar-benar menginginkan kijang kencana itu.
Anyway, good night, kekasih.
—Rama
Previous Next